Pameran Tunggal: Bertimbang Taruh
Leonardiansyah Allenda
Opening:
14 August 2014, 7.30 PM
Exhibition:
15 August - 6 September 2014, 9 AM - 5 PM
Closed on Sunday & Monday
Discussion:
5 September, 7.30 PM
Cemeti Art House
D.I. Panjaitan 41, Yogyakarta
Tulisan ini untuk pengantar Pameran Bertimbang Taruh
Bagaimana menyamakan harga atau nilai dari sebuah pertaruhan, jika yang dipertaruhkan bukanlah uang, melainkan sesuatu yang memiliki ukuran serta tafsir berbeda, namun keduanya sama penting, sama-sama bernilai, sama-sama punya bobot. Ukuran apa yang lantas pantas untuk membuat keduanya bertaruh setimbang?
Pertanyaan itulah yang saya temukan dalam karya-karya Leo yang di pamerkan di Cemeti, Yogjakarta, Agustus 2014. Sembilan karya yang ditampilkan seperti sedang mencari cara 'Bertimbang Taruh' atas nilai-nilai yang membentuk dan meruang dalam diri dan kekaryaan Leoandriansyah Allenda.
Leo lahir dan dibesarkan dari keluarga Cina dan Arab pedagang di Banyuwangi dimana pertukaran nilai dan pertaruhan menjadi nafas hidup sehari-hari. Tidak hanya uang yang menjadi nilai yang dipertukarkan dan dipertaruhkan, namun lebih dalam lagi nilai-nilai budaya yang berbeda, terus menerus bernegosiasi untuk menemukan nilai pertukaran dan pertaruhannya. Situasi seperti itulah yang membuat Leo terus menerus mempertanyakan, mencari cara untuk menakar dan mengukur nilai-nilai itu lewat karya-karyanya.
Bagaimana menentukan yang satu lebih berharga dari yang lain ketika keduanya sama-sama berharga. Bagaimana menentukan keduanya sama-sama berharga ketika salah satu justru menunjukkan sisi kekurangannya. Dalam keseharian Leo dengan latar belakang kultural dan sistem nilai yang rumit juga kompleks, ukuran terejawantahkan dalam simbol-simbol materialisme (benda-benda dan juga uang) yang lebih mudah terukur serta terlihat. Kekayaan materi seringkali menjadi penentu bobot atau nilai sebuah simbol bahkan status sosial dalam masyarakat, daripada kedalaman makna yang terkandung dari nilai budaya itu sendiri.
Bagi saya menengok dan mencoba memahami dialektika latar belakang budaya serta tegangan nilai-nilai itu, justru menjadi modal penting untuk berkomunikasi dengan karya-karya Leo. Di sela-sela dialektika itulah, saya seperti menemukan pertentangan sekaligus peluang. Di balik bentukan-bentukan karya yang rigid, kaku, sistematis, presisi dan seolah tidak bisa ditawar, saya justru menemukan peluang negosiasi dan kesepakatan karena alat ukur serta satuan ukuran yang Leo gunakan, memiliki kelenturan dan relativitasnya sendiri.
Misalnya saja pada karya timbangan. Leo menyusun lima timbangan mulai dari timbangan seukuran manusia (bisa mengukur berat tubuh manusia) hingga yang terkecil (milligram). Kelimanya disusun dalam satu titik keseimbangan dengan material besi, kayu dengan karakter yang kaku, keras, solid. Ketika karakter material itu menjadi alat ukur, justru menemukan dinamikanya sendiri, sehingga ketika menambah sedikit beban pada yang terkecil atau yang mana saja, semua akan ikut bergerak. Timbangan menjadi hal yang mewakili cara Leo berpikir tentang nilai materi dan nilai atas tubuhnya (keberadaan dan kehadirannya). Keterikatan dan kait berkait setiap unsur dan materi dalam timbangan menjadi satu kesatuan yang membentuk kesetimbangan itu sendiri. Satuan ukuran dalam timbangan, seolah menjadi acuan untuk lebih presisi dalam memberikan penilaian atas apa yang berkecamuk dalam diri dan pikirannya.
Karya ayakan (saringan) mencoba mewakili bagaimana kawat-kawat besi terjalin membentuk kisi-kisi, menjadi kesatuan penanda ukuran, bergerak dalam kebakuannya, seperti mencoba mencari berapa nilai terbaik yang bisa ditakar. Ketika menyaring, kita dapat melihat semua materi bergeser kesana-sini, memisahkan tubuhnya dengan tubuh lain dan menemukan definisi baru sebagai yang terpilih dan yang tidak terpilih.
Realitas dua dimensi yang di proyeksikan lewat video melengkapi karya ini, seolah ingin memberikan gambaran utuh bahwa soal menakar ini bukan sekedar hitung menghitung di atas kertas atau penyederhanaan subjek ke dalam satuan ukuran atau pengkategorian 'terpilih' ataupun 'tidak terpilih', namun juga bagaimana takaran itu menubuh dan menjadi laku keseharian dan bergerak menemukan keseimbangannya diantara takaran-takaran yang berbeda.
Kain merah dan putih dengan lampu kuning yang meleburkan bias cahaya dari kedua warna itu, mewakili kehidupan nyata bahwa pada jarak tertentu, semua takaran, satuan ukuran, juga nilai-nilai yang diterakan, bisa saja melebur menghilangkan sekat-sekat pembedanya. Namun jika kembali didekati, serat kain linen menjadi penyaring (ayakan) cahaya lampu dan membentuk bayangan baru yang ditangkap mata. Pendaran cahaya yang menembus serat-serat linen itu seolah menyadarkan bahwa tak ada satupun di dunia ini yang telepas dari saringan nilai yang membuat satu benda atau hal yang sama akan selalu memiliki nilai berbeda-beda bagi setiap orang. Dan tanpa disadari, setiap hari adalah proses menyaring apapun yang bergulir dalam kehidupan kita. Persis seperti kerja sebuah ayakan.
Secara metafor Leo sepertinya ingin ‘menyerap angka-angka dalam tubuh’, menciptakan ruang dan membekukan waktu dengan cara mengambil yang tersaring dan membuang yang tidak tersaring, untuk merasakan pengalaman 'menjadi kosong'. Dalam kekosongan itulah seringkali ukuran, nilai-nilai, takaran justru menjadi nampak jelas, menemukan satuannya.
***
Ketika memberi nilai pada benda-benda mati, tidak bergerak, statis dan memiliki berat jenis, lebih mudah menemukan kesepakatan satuan nilai untuk menghitungnya, karena apa yang dinilai relatif tidak berubah dan konstan. Namun persoalan yang kerap muncul dan membuat gamang, ketika yang dinilai adalah konsep dan kesepakatan itu sendiri. Bagaimana kesepakatan dinilai oleh 'konsep yang juga hasil dari kesepakatan'. Dimana setiap kesepakatan selalu membawa konsekuensi lahirnya kesepatakan-kesepakatan lain. Kesepakatan dengan karakternya yang jamak, majemuk dan tidak tunggal, menimbulkan persoalan ketika mesti menentukan cara dan ukuran untuk menilainya. Untuk itu, uang dengan nilai nominalnya, seringkali menjadi alat ukur yang 'dianggap' sebanding dan memudahkan pada saat nilai itu harus ditetapkan. Padahal nilai nominal uang, seringkali tidak menjawab secara presisi pertanyaan yang ada. Justru uang seringkali mengabaikan dan mendangkalkan kedalaman nilai imaterial (yang juga sulit diukur seberapa dalam).
Kerumitan yang sama, ketika Leo berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan 'Apakah seni itu?'. Selama ini, Institusi menjadi satuan ukuran nilai untuk menimbang apakah sebuah karya dapat disebut sebagai seni atau bukan. Bermacam orang dan kepentingannya lantas membuat ruang-ruang seni dan menjadikannya wakil dari institusi untuk membentuk persepsi orang tentang apa yang disebut seni. Dalam kerangka pertukaran nilai, Apakah seni itu adalah sebuah karya yang kemudian mendapatkan nilai nominal lebih besar daripada yang lain?
Rasanya soal memberi nilai pada yang dianggap seni dan yang bukan, masih membingungkan bukan hanya Leo, tapi juga kebanyakan dari kita.
***
Mencermati karya-karya Leoadriansyah Allenda, membawa saya pada pemahaman bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa lepas dari penilaian dan pengukuran. Bahkan hal-hal yang tidak dapat terukurpun selalu mencari cara untuk dapat menemukan alat ukurnya. Namun ketika alat ukur itu sendiri mengandung ketidak pastian nilai, saya jadi bertanya-tanya: 'Seperti apakah nilai yang bertimbang ?' Bagaimana menemukan nilai pertaruhan yang sama, jika uang tidak lagi menjadi alat ukurnya? .




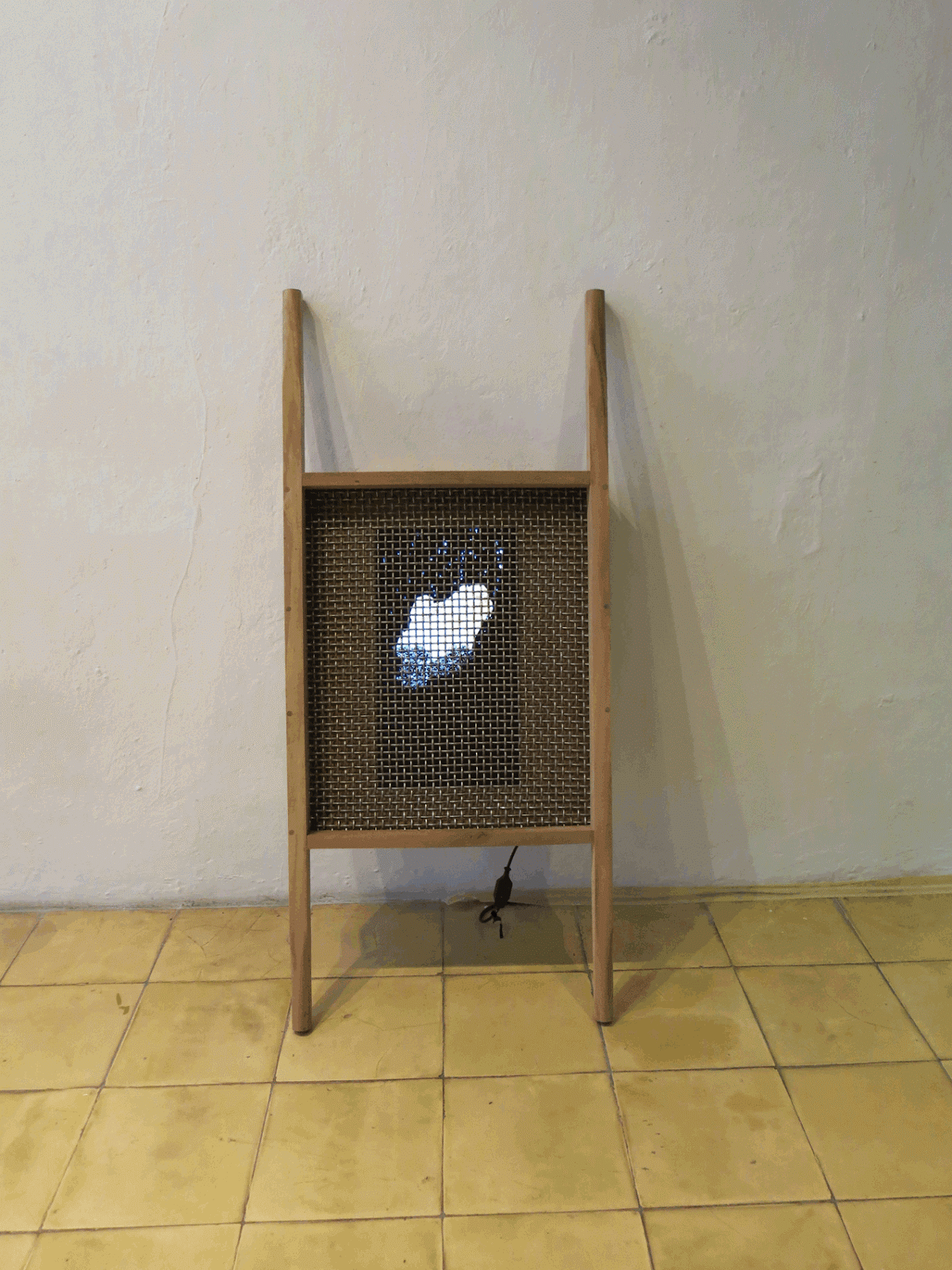

Comments